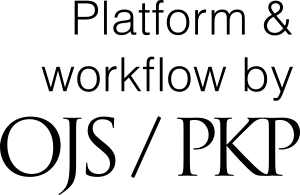Pernikahan Sementara dalam Hukum Iran: Dasar Hukum, Implikasi Gender, dan Perspektif Jurisprudensial
Keywords:
Pernikahan sementara, hukum Iran, jurisprudensi Syiah Imamiyyah, studi gender, feminisme Islam, mutʿah, hukum keluargaAbstract
Pernikahan sementara (mutʿah atau sigheh) memiliki tempat yang khas namun kontroversial dalam hukum keluarga Iran, yang berakar pada jurisprudensi Syiah Imamiyyah dan tercantum dalam Pasal 1075–1077 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Iran. Meskipun secara hukum dan teologis disahkan, mutʿah mengungkapkan keberlanjutan hierarki patriarkal dalam sistem status pribadi Iran. Berdasarkan penelitian etnografis Shahla Haeri dalam Law of Desire (1989) dan kritik hukum Ziba Mir-Hosseini dalam Marriage on Trial (1993), artikel ini mengkaji bagaimana institusi ini mengubah kedekatan menjadi kontrak berbasis gender yang memprivilegiakan otoritas pria dan membatasi otonomi perempuan. Menggunakan konsep Simone de Beauvoir tentang perempuan sebagai “Yang Lain” dan kritik Fatima Mernissi terhadap politik seksual Islam, penelitian ini berargumen bahwa mutʿah berfungsi sebagai mekanisme yuridis yang mengkomodifikasi agensi perempuan dengan kedok legitimasi agama. Dari perspektif keadilan gender, mutʿah mengungkapkan ketidakseimbangan struktural dalam hak perceraian, pemeliharaan, dan warisan yang mencerminkan epistemologi patriarkal yang lebih dalam dalam jurisprudensi Islam. Ketidaksetaraan ini tidak hanya terbatas pada pernikahan sementara, tetapi juga meresap ke dalam pernikahan permanen (nikāḥ dāʾim) dan logika fiqh yang lebih luas, di mana pria mempertahankan hak sepihak untuk bercerai (ṭalāq), poligini, dan perwalian (qiwāmah). Pola ini menekankan adanya hierarki gender yang tertanam dalam tradisi Sunni dan Syiah. Sebagai respons, ulama Syiah kontemporer membela mutʿah sebagai institusi yang disahkan Tuhan untuk mengatur hasrat manusia, mencegah hubungan yang tidak sah, dan menjaga keteraturan moral. Pemikir seperti al-Ṭūsī dan al-Ṣadr berpendapat bahwa ketidakseimbangan gender mencerminkan keadilan ilahi (ʿadl ilāhī) dan peran sosial yang terbedakan, bukan ketidakadilan, dengan demikian menempatkan institusi ini dalam kerangka besar jurisprudensi etis. Pembelaan ini menyoroti perbedaan epistemik yang dalam antara pembacaan reformis yang berorientasi pada kesetaraan gender dalam hukum Islam dan interpretasi tradisional yang berlandaskan teori perintah ilahi. Pada akhirnya, untuk memajukan keadilan gender dalam hukum Iran, tidak hanya perlu merevisi aspek prosedural mutʿah, tetapi juga meninjau kembali dasar teologis dan filosofis yang mendasari ketidaksetaraan gender dalam pemikiran hukum Islam.